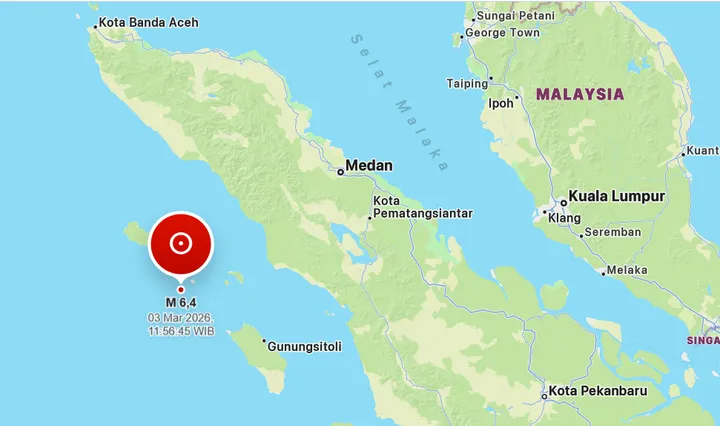Empati dunia terhadap Rohingya memiliki batas waktu, dan seiring berjalannya siklus berita, perhatian dan dana untuk salah satu minoritas yang paling menderita di dunia pun ikut berkurang.
Di tengah kekosongan lupa ini, muncul “Lost Land” atau “Hara Watan”, nama aslinya dalam bahasa Rohingya, sebuah film yang baru-baru ini ditayangkan di Festival Film Bosphorus ke-13 di Istanbul, bertujuan menjadi obat penawar yang kuat terhadap amnesia kolektif tersebut.
Film ini mengikuti dua anak Rohingya, kelompok minoritas Muslim dari Myanmar yang secara sistematis ditolak kewarganegaraannya dan menghadapi penganiayaan brutal, yang menyebabkan eksodus massal.
Bagi sutradara Jepang Akio Fujimoto, kunjungan ke festival ini merupakan tonggak pribadi. Ia mengatakan kepada TRT World bahwa ia “sudah lama mengagumi film-film Turki, termasuk karya Semih Kaplanoglu, dan ingin mengunjungi Türkiye suatu hari nanti”. Ia mengekspresikan apresiasi mendalam terhadap “warisan budaya Istanbul yang kaya”, dan mengatakan ia “sangat menikmati waktunya” di sini.
Filmnya, bagaimanapun, menceritakan kisah pengungsian jauh dari pusat-pusat budaya. Sebuah produksi bersama antara Jepang, Prancis, Jerman, dan Malaysia, “Lost Land” mengangkat kisah Rohingya dari sudut pandang yang paling rentan: anak-anak.
Rohingya yang telah lama menderita
Proyek ini lahir dari 12 tahun kerja film Fujimoto di Asia Tenggara, “terutama di Myanmar,” tempat Rohingya tinggal selama berabad-abad sebelum diusir oleh otoritas setempat.
Dia mengatakan kepada TRT World bahwa pembicaraan terbuka tentang Rohingya yang masih tinggal di sana, yang hidup dalam kondisi yang mengenaskan, adalah “tabu,” dan dia awalnya menahan diri untuk tidak bekerja pada film tersebut karena “takut kehilangan pekerjaan dan teman-temannya di negara itu.”
Namun, seiring dia mengikuti laporan tentang penganiayaan mereka, posisinya menjadi tidak dapat dipertahankan. “Saya merasa malu karena telah mengabaikan suara mereka dan merasa bersalah yang mendalam,” ungkapnya. Rasa bersalah itu menjadi dorongan utama di balik “Lost Land.”
Keaslian mendalam film ini berasal dari para pemerannya. Fujimoto meng casting lebih dari 200 orang Rohingya, tidak ada yang merupakan aktor terlatih, dan film ini adalah yang pertama kali menggunakan bahasa Rohingya sebagai bahasa utama.
“Orang Rohingya tidak dapat berkomunikasi melalui bahasa tertulis, semua arahan di lokasi syuting diberikan secara lisan,” kata Fujimoto. Meskipun demikian, dan sutradara hanya berbicara bahasa Jepang, ia melaporkan bahwa “hampir tidak ada masalah komunikasi.”
Cerita ini mengikuti dua saudara kandung muda, seorang gadis berusia sembilan tahun bernama Somira dan adik laki-lakinya yang berusia empat tahun, Shafi.
Setelah meninggalkan rumah sementara mereka di Bangladesh untuk mencapai Malaysia, mereka ditinggalkan oleh penyelundup manusia di Thailand. Terpisah dari pengasuh dewasa mereka, mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan dan menyeberangi sungai sendirian, didukung oleh bantuan dari sesama wisatawan dan penduduk lokal yang baik hati.
Motif visual yang menyentuh menghubungkan perjalanan mereka: jersey Adidas berwarna saffron milik Somira, yang kemudian diulang oleh selimut berwarna saffron yang membungkus adiknya, Shafi.
‘Orang-orang tanpa status kewarganegaraan’
“Menggambarkan perjalanan mereka sangat penting untuk mengungkapkan realitas Rohingya — orang-orang tanpa kewarganegaraan atau status kewarganegaraan,” kata Fujimoto dalam Pernyataan Sutradara untuk Venice Biennale, di mana film tersebut memenangkan Hadiah Juri Khusus. Mereka, katanya, “dipaksa hidup dalam kondisi yang tidak stabil di mana pun mereka pergi, selalu mencari tempat di mana mereka benar-benar merasa menjadi bagian dari sesuatu.”
Kondisi tanpa kewarganegaraan ini bukan hanya tema dalam film, tetapi juga kenyataan bagi para pemeran utamanya. Saudara kandung Rohingya asli, Shomira Rias Uddin dan Muhammad Shofik Rias Uddin, yang memerankan Somira dan Shafi masing-masing, tidak dapat mendampingi Fujimoto ke Festival Bosphorus di Istanbul.
Alasannya adalah ringkasan yang gamblang tentang penderitaan mereka: “ mereka tidak diakui sebagai pengungsi di negara mana pun… dan tetap berada dalam posisi yang rapuh dan tidak stabil,” tanpa paspor untuk bepergian.
Fujimoto berharap filmnya dapat menjembatani jarak tersebut. Ia menyimpulkan dengan mengatakan, “Jika sinema adalah bentuk seni yang dapat berfungsi sebagai metafora untuk ‘hidup bersama’, saya harap melalui film ini, Rohingya — yang mungkin tampak jauh bagi banyak orang — dapat merasa lebih dekat dengan kita, sebagai tetangga, sebagai teman.”