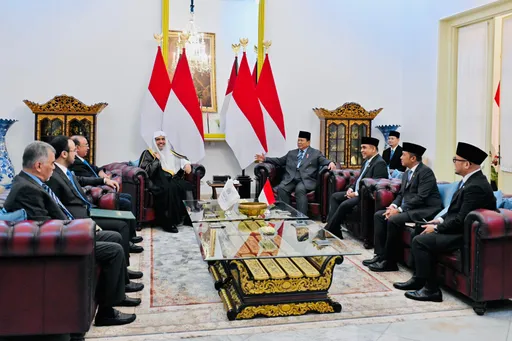Ada pepatah, yang dikaitkan dengan Edward Said, pemikir dan aktivis Palestina-Amerika, tentang perlunya menggunakan ‘kekuatan budaya di atas budaya kekuasaan.’
Saya pertama kali menemukannya pada perjalanan kedua saya ke Palestina pada Mei 2008, sebagai bagian dari kelompok tokoh budaya dan penulis yang mengikuti edisi pertama Palestine Literary Festival.
Saat itu, Gaza baru saja diblokade dan akan menghadapi serangan militer pertamanya. Tembok apartheid di Tepi Barat yang diduduki belum sepenuhnya dibangun. Ehud Olmert menjabat sebagai perdana menteri, dan Benjamin Netanyahu akan memulai pemerintahan hampir tanpa henti yang membawa kita ke genosida yang kita saksikan hari ini.
Pada 2008, Palestina adalah topik tabu di ruang-ruang budaya, terkunci dalam keheningan oleh tuduhan anti-Semitisme.
Bahkan penggunaan kata ‘apartheid’ untuk menggambarkan sistem pendudukan Israel dianggap kontroversial, meski pada 2004 International Court of Justice menyatakan pembangunan tembok Israel di Tepi Barat yang diduduki ilegal menurut hukum internasional. Saat itu, populasi pemukim di Tepi Barat yang diduduki berjumlah 290.697; kini melebihi 700.000.
Anda tidak perlu menatap jauh ke belakang untuk melihat bagaimana ketidakadilan yang berlangsung selama tujuh belas tahun terakhir telah membawa kita pada bencana saat ini.
Dekade impunitas, didorong oleh miliaran kontrak militer dari AS, Jerman, Italia, dan Inggris, menciptakan kesombongan Netanyahu yang sekarang mampu berbicara di Majelis Umum PBB yang hampir kosong, seolah opini dunia tak berarti.
Namun sebenarnya penting. Budaya kekuasaan telah menciptakan fakta-fakta yang tak terbantahkan di lapangan. Tetapi legitimasi Israel di panggung dunia telah hancur.
Jika dunia memahami ketidakadilan Israel terhadap Palestina pada 2008, atau bahkan lebih awal, apa yang bisa kita hindari hari ini? Mungkin serangan 7 Oktober 2023 tidak akan terjadi. Mungkin beberapa politisi dunia tidak akan terpilih tanpa catatan solidaritas dengan Palestina, bukan sebaliknya.
Mungkin terdengar naif untuk menanyakan pertanyaan masa lalu, tetapi ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan tentang masa depan. Salah satu kemajuan utama dalam dua dekade terakhir adalah kekuatan budaya: melalui seni, sastra, film, musik, dan gerakan solidaritas global.
Harga genosida ini tak terbayangkan tinggi. Namun jika Holocaust menjadi faktor terciptanya kondisi bagi pembentukan Israel dan pengusiran Palestina dalam Nakba 1948, tidaklah berlebihan untuk bertanya apakah genosida di Gaza bisa menciptakan kondisi bagi solusi berbeda, yang berlandaskan hukum internasional dan hak yang setara.
Politik berada di hilir budaya. Menjadi bagian dari solidaritas pembebasan Palestina sambil berusaha menghentikan genosida sungguh menyakitkan, karena keseimbangan kekuatan nyata sangat condong ke arah ketidakadilan. Namun kesadaran global akhirnya bergeser, setelah 77 tahun.
1948 juga tahun penting bagi Afrika Selatan. Tahun itu menegaskan hukum apartheid yang baru dicabut pada 1991. Perlawanan di Afrika Selatan tentu menjadi inti perjuangan, dan peristiwa besar, seperti berakhirnya Perang Dingin, memengaruhi jalannya pembebasan.
Namun tak diragukan lagi bahwa kekuatan budaya, dan gerakan boikot anti-apartheid saat itu, memainkan peran besar dalam perubahan tersebut.
Bagaimana budaya membentuk perubahan
Perjuangan pembebasan tidak pernah linier, dan masa depan sering muncul dari tempat yang tak terduga.
Tiga puluh lima tahun setelah gerakan boikot Afrika Selatan dimulai, titik balik penting terjadi ketika Mary Manning, seorang pekerja toko berusia 21 tahun, menolak menangani penjualan grapefruit di sebuah supermarket di Dublin.
Tindak solidaritasnya itu memicu pemogokan yang akhirnya menarik perhatian Uskup Agung Desmond Tutu ke Dublin, yang mengubah citra bentuk ketidakpatuhan sipil yang saat itu sangat tidak populer, sebagaimana umumnya boikot. Dua tahun kemudian, Irlandia menjadi pemerintah Barat pertama yang memberlakukan larangan penuh terhadap barang-barang Afrika Selatan.
Hari ini, solidaritas dengan Palestina meningkat secara global—dari pekerja pelabuhan di Italia yang memblokir pengiriman senjata ke Israel, hingga 5.000 penandatangan Filmworkers Pledge yang menolak bekerja dengan institusi Israel yang bersalah, dari Global Sumud Flotilla yang mencoba menyalurkan bantuan ke Gaza, hingga konser penggalangan dana terbesar untuk Palestina di Wembley Arena, Inggris, hingga boikot konsumen di supermarket dan tuntutan kepada UEFA, FIFA, dan Eurovision. Semua protes ini berlangsung di jalanan setiap kota besar di dunia, dengan selebriti, penulis, dan musisi bergabung dalam seruan Free Palestine—mungkin kita akan melihat masa ini sebagai titik balik.
Untuk pertama kalinya sejak 1948, tahun dimulainya Nakba, ketika ratusan ribu warga Palestina pertama kali dibersihkan secara etnis, pemahaman atas pengalaman Palestina tidak lagi abstrak; ia dirasakan.
Ratusan juta, bahkan mungkin miliaran orang, menangis melihat anak-anak, ibu, dan ayah menghadapi hal yang tak terbayangkan, sementara kita bersama-sama menuntut dunia yang berbeda.
Dekade mendatang, tahun-tahun mendatang, adalah kesempatan bagi kekuatan budaya untuk masuk ke dunia politik dan mengubahnya.
Setiap perjuangan pembebasan di masa lalu menempuh jalan yang kadang frustrasi dan tak linier menuju keadilan, tercoreng, dipenjara, dan dihina, tetapi di ujung perjalanan panjang ada kebebasan, dan kebanggaan luar biasa karena telah mengambil risiko untuk menjadi bagian darinya.
Seperti kata Nelson Mandela, itu selalu tampak mustahil sampai tercapai.