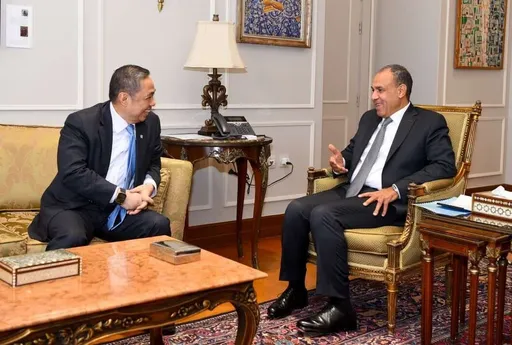Dalam sepekan terakhir, jet tempur Arab Saudi melancarkan sejumlah serangan udara di Provinsi Hadramaut, Yaman, dengan sasaran posisi yang terkait dengan Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC), kelompok separatis yang didukung Uni Emirat Arab (UEA).
Arab Saudi juga secara terbuka menuduh Uni Emirat Arab—sesama negara Teluk sekaligus mantan sekutu dalam perang saudara Yaman—melakukan tindakan yang dinilai mengancam keamanan nasionalnya.
Serangan dan tudingan ini melampaui sekadar insiden di medan tempur. Situasi tersebut mencerminkan retakan terbuka dalam apa yang dulu digambarkan sebagai intervensi Teluk yang solid di Yaman, sekaligus menjadi peringatan bahwa strategi regional yang lebih luas kini mulai runtuh.
UEA semakin mengandalkan milisi proksi, mitra bersenjata lokal, dan struktur keamanan paralel untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya.
Pendekatan ini memang menghasilkan keuntungan taktis jangka pendek, termasuk memperluas pengaruh Emirat di sepanjang garis pantai strategis, pelabuhan, dan koridor perdagangan.
Namun, strategi itu juga mempercepat tren yang lebih berbahaya: normalisasi fragmentasi yang disokong negara di sejumlah negara Timur Tengah yang paling rapuh.
Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar perselisihan antarsekutu. Ini adalah perebutan cara kekuasaan dijalankan di kawasan yang sudah terkuras oleh perang.
Penggunaan pasukan proksi yang kian masif oleh UEA menandai pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuatan regional. Berbeda dengan intervensi tradisional yang bertujuan menopang pemerintah pusat, Abu Dhabi justru berinvestasi membina aktor-aktor bersenjata yang beroperasi berdampingan, atau bahkan berseberangan, dengan institusi negara.
Di Yaman, dukungan Emirat terhadap STC secara efektif menciptakan otoritas tandingan terhadap pemerintah yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi.
Di seluruh kawasan Laut Merah, model ini lebih memprioritaskan penguasaan wilayah, pelabuhan, dan simpul-simpul keamanan ketimbang membangun kembali tata kelola negara yang berdaulat.
Bahaya yang mengintai bukan hanya ketidakstabilan di masing-masing negara, melainkan preseden yang sedang dibentuk.
Ketika kekuatan regional secara terbuka mensponsori milisi demi mengamankan pengaruh, fragmentasi berubah menjadi kebijakan, bukan lagi gejala.
Negara tidak lagi menjadi unit dasar tatanan; sebaliknya, jaringan bersenjata dan tokoh kuat lokal menjadi mata uang kekuasaan.
Seiring waktu, risiko ini membentuk ulang politik Timur Tengah menjadi lanskap di mana batas negara makin tak berarti dibanding loyalitas, dan aktor eksternal lebih memilih mengelola ketidakstabilan ketimbang menyelesaikannya.
Memperluas arena persaingan
Tak ada tempat yang menunjukkan pergeseran ini sejelas Yaman.
Koalisi pimpinan Arab Saudi awalnya dibentuk dengan tujuan strategis yang jelas: melawan Houthi dan, secara tidak langsung, membatasi perluasan pengaruh Iran di sepanjang Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb—salah satu titik sempit maritim paling krusial di dunia.
Yaman bukan sekadar konflik domestik, melainkan juga garis depan dalam perebutan keseimbangan kekuatan regional yang lebih luas.
Selama beberapa tahun, Arab Saudi dan UEA tampak sejalan dengan tujuan tersebut.
Namun seiring waktu, terutama dalam setahun terakhir, fokus konflik bergeser secara halus namun menentukan.
Ketika tekanan militer Amerika Serikat–Israel terhadap Houthi meningkat dan Iran menerima serangan langsung maupun tidak langsung di berbagai kawasan, persepsi ancaman langsung yang dulu menyatukan koalisi mulai memudar.
Sebagai gantinya, muncul garis patahan baru—kali ini di dalam koalisi itu sendiri.
Serangan udara terbaru Arab Saudi di Hadramaut menegaskan sejauh mana perbedaan ini telah melebar.
Riyadh kini memandang dominasi militer dan politik STC yang kian menguat di Yaman timur dan selatan sebagai tantangan langsung terhadap kepentingan keamanannya serta prinsip negara Yaman yang bersatu.
Abu Dhabi, sebaliknya, tampak semakin bersedia menoleransi—atau bahkan memfasilitasi—Yaman yang terfragmentasi, selama hal itu menjamin mitra yang dapat diandalkan di sepanjang pesisir dan pengaruh berkelanjutan atas pelabuhan serta jalur maritim utama.
Apa yang bermula sebagai kampanye terkoordinasi melawan Houthi pun berevolusi menjadi kontestasi yang jauh lebih kompleks.
Yaman kini bukan hanya arena perang saudara berkepanjangan, tetapi juga panggung rivalitas intra-Teluk, di mana para mantan sekutu mengejar tujuan akhir yang berbeda.
Dampaknya adalah kebuntuan diplomatik dan meningkatnya volatilitas di lapangan, sementara jutaan warga Yaman tetap terjebak dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Arab Saudi memandang stabilitas di sepanjang Laut Merah sebagai kepentingan nasional inti.
Mesir sangat peka terhadap setiap perkembangan yang berpotensi memengaruhi keamanan Sungai Nil dan keseimbangan militer regional. Iran, di sisi lain, menunjukkan minat yang kian besar untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan di jalur-jalur maritim.
Dalam lingkungan strategis yang padat ini, sikap asertif UEA berisiko memperuncing rivalitas alih-alih mengelolanya.
Persaingan pengaruh dapat dengan cepat bergeser menjadi eskalasi perang proksi, terutama di negara-negara yang institusinya telah runtuh.
Keuntungan jangka pendek, biaya jangka panjang
Tak dapat disangkal, pendekatan UEA telah membuahkan hasil. Pasukan proksi lebih murah dibanding pengerahan militer langsung, mudah disangkal secara politik, dan sering kali lebih adaptif terhadap kondisi lokal.
Mereka dapat mengamankan pelabuhan, menekan lawan, dan membentuk hasil politik tanpa beban pendudukan.
Namun keuntungan ini datang dengan harga. Milisi yang telah diberdayakan jarang tetap patuh. Kepentingan mereka berubah, ambisi membesar, dan akuntabilitas memudar.
Sejarah kawasan—dari Lebanon hingga Libya—memberi banyak peringatan tentang apa yang terjadi ketika kelompok bersenjata melampaui kendali patronnya.
Jika kekuatan yang didukung UEA di Yaman menjadi tak terkendali, dampaknya tidak akan bersifat lokal.
Efeknya akan merambat ke jalur perdagangan, pasar energi, dan arsitektur keamanan regional. Negara yang terfragmentasi tidak menyerap ketidakstabilan; mereka mengekspornya.
Serangan udara Arab Saudi di Hadramaut bisa menjadi titik balik. Langkah ini mengisyaratkan bahwa Riyadh tak lagi bersedia secara diam-diam mengakomodasi strategi proksi Abu Dhabi ketika bertabrakan dengan kepentingan inti Saudi.
Secara lebih luas, situasi ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman bagi para pemegang kekuasaan kawasan.
Apakah Timur Tengah bergerak menuju masa depan di mana pengaruh dijalankan melalui milisi, bukan institusi?
Bisakah negara-negara rapuh bertahan ketika aktor eksternal lebih mengutamakan leverage ketimbang legitimasi?
Dan berapa banyak perang proksi yang tumpang tindih dapat diserap kawasan ini sebelum konflik-konflik lokal melebur menjadi sesuatu yang jauh lebih besar?
UEA bukan satu-satunya pemain dalam permainan ini. Namun negara tersebut telah menjadi salah satu pelakunya yang paling piawai—dan itu membuat setiap pilihannya memiliki konsekuensi besar.
Keuntungan keamanan jangka pendek yang diraih melalui fragmentasi mungkin terasa menggoda. Namun di kawasan yang telah lama dilukai oleh keruntuhan negara, konsekuensi jangka panjangnya bisa sangat menghancurkan.
Yaman bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia adalah peringatan tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan dikejar tanpa tujuan akhir yang jelas.
Pertanyaannya kini: apakah para pemimpin kawasan menyadari bahaya tersebut, atau justru terus melangkah di jalur yang menjadikan proksi hari ini sebagai api tak terkendali di masa depan.